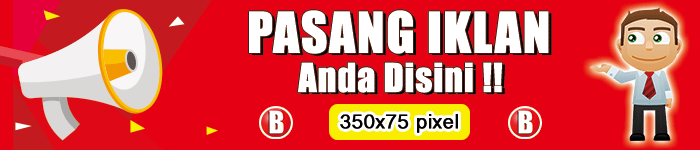Jempolindo.id – Indonesia, negeri yang kaya akan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal, kini terus bergulat dengan persoalan korupsi yang seakan tak kunjung usai.
Data Transparency International tahun 2023 mencatat Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI), menunjukkan bahwa praktik koruptif masih menjadi momok serius.
Di tengah upaya pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum, banyak pengamat menyoroti faktor budaya sebagai akar masalah. Salah satunya adalah memudarnya budaya malu —sebuah nilai tradisional yang dahulu menjadi benteng moral masyarakat—dalam menyikapi perilaku korupsi.
Budaya Malu: Dari Pengikat Sosial ke Ambang Kepunahan
Budaya malu (shame culture) merupakan konsep sosial di mana individu menghindari perbuatan tercela karena takut mendapat sanksi moral dari lingkungan sekitar.
Nilai ini mengajarkan bahwa tindakan negatif bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga mempermalukan keluarga, komunitas, dan leluhur. Di Aceh, misalnya, budaya peumalè (malu) menjadi mekanisme kontrol untuk mencegah pelanggaran norma. Begitu pula di Bali, konsep lek (malu) menjadi alat penjaga keharmonisan sosial.
Namun, dalam beberapa dekade terakhir, budaya malu mulai tergerus oleh perubahan zaman. Modernisasi, globalisasi, dan individualisme menggeser orientasi masyarakat dari nilai kolektif ke kepentingan pribadi.
“Dulu, seorang pejabat yang korupsi akan dijauhi oleh warga kampungnya sendiri. Sekarang, mereka justru dielu-elukan karena dianggap ‘berhasil’ secara materi,” ujar seorang pengamat budaya dari Universitas Gadjah Mada.
Korupsi dan Hilangnya Rasa Malu
Memudarnya budaya malu berbanding lurus dengan maraknya korupsi. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, pada 2022 saja, terdapat 226 laporan dugaan korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp5,7 triliun.
Kasus-kasus tersebut melibatkan pejabat tinggi, anggota legislatif, hingga aparat desa. Ironisnya, banyak tersangka korupsi yang tetap tersenyum saat diborgol, seolah tak ada rasa bersalah atau malu.
Fenomena ini mencerminkan degradasi moral yang parah. Dalam budaya malu, koruptor seharusnya merasa tercela karena telah mengkhianati kepercayaan publik. Namun, saat ini, korupsi kerap dianggap sebagai “budaya hadiah” atau bagian dari sistem yang wajar.
“Masyarakat mulai memaklumi korupsi kecil-kecilan, seperti ‘uang rokok’ untuk mengurus dokumen. Akibatnya, rasa malu hilang, dan korupsi menjadi normal,” jelas sosiolog dari Universitas Indonesia.
Dampak Sosial: Ketidakpercayaan dan Ketimpangan
Korupsi tidak hanya merugikan ekonomi negara, tetapi juga merusak sendi-sendi sosial. Survei LSI 2023 menunjukkan 78% masyarakat tidak percaya pada integritas politisi. Ketidakpercayaan ini memicu apatisme publik, melemahkan partisipasi dalam pengawasan, dan akhirnya memperpanjang lingkaran korupsi.
Di sisi lain, korupsi memperlebar ketimpangan. Dana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang seharusnya dinikmati rakyat justru mengalir ke kantong segelintir elit.
Revitalisasi Budaya Malu: Antara Hukum dan Pendidikan Moral
Untuk memutus mata rantai korupsi, penegakan hukum melalui KPK dan pengadilan memang krusial. Namun, tanpa upaya mengembalikan budaya malu, langkah ini hanya menjadi tameng temporer.
Beberapa langkah strategis bisa diambil:
1. Pendidikan Karakter sejak Dini
Integrasikan nilai-nilai budaya malu dalam kurikulum sekolah. Anak-anak perlu diajari bahwa korupsi bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga memalukan keluarga dan bangsa.
2. Peran Tokoh Masyarakat dan Agama:
Ulama, adat, dan tokoh lokal harus aktif mengampanyekan kembali budaya malu melalui ceramah, tradisi, dan sanksi sosial.
3. Media dan Kampanye Publik:
Media massa perlu gencar memberitakan kasus korupsi bukan sekadar sebagai sensasi, tetapi dengan perspektif budaya—menyoroti aib yang ditimbulkan pelaku.
Kesimpulan: Malu sebagai Tameng Moral
Korupsi adalah kejahatan multidimensi yang membutuhkan pendekatan holistik. Di samping hukum yang tegas, revitalisasi budaya malu bisa menjadi senjata ampuh untuk membangun kesadaran kolektif.
Seperti kata pepatah Jawa, “Ajining diri soko lathi, ajining rogo soko busono” (harga diri berasal dari perkataan, harga tubuh berasal dari pakaian). Jika setiap individu merasa malu untuk korupsi, maka bangsa ini bisa kembali pada jati dirinya yang jujur dan bermartabat.
Membangun budaya antikorupsi bukanlah kerja instan. Namun, selama ada komitmen untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur, harapan untuk Indonesia yang bersih tetap mungkin diwujudkan. (#)